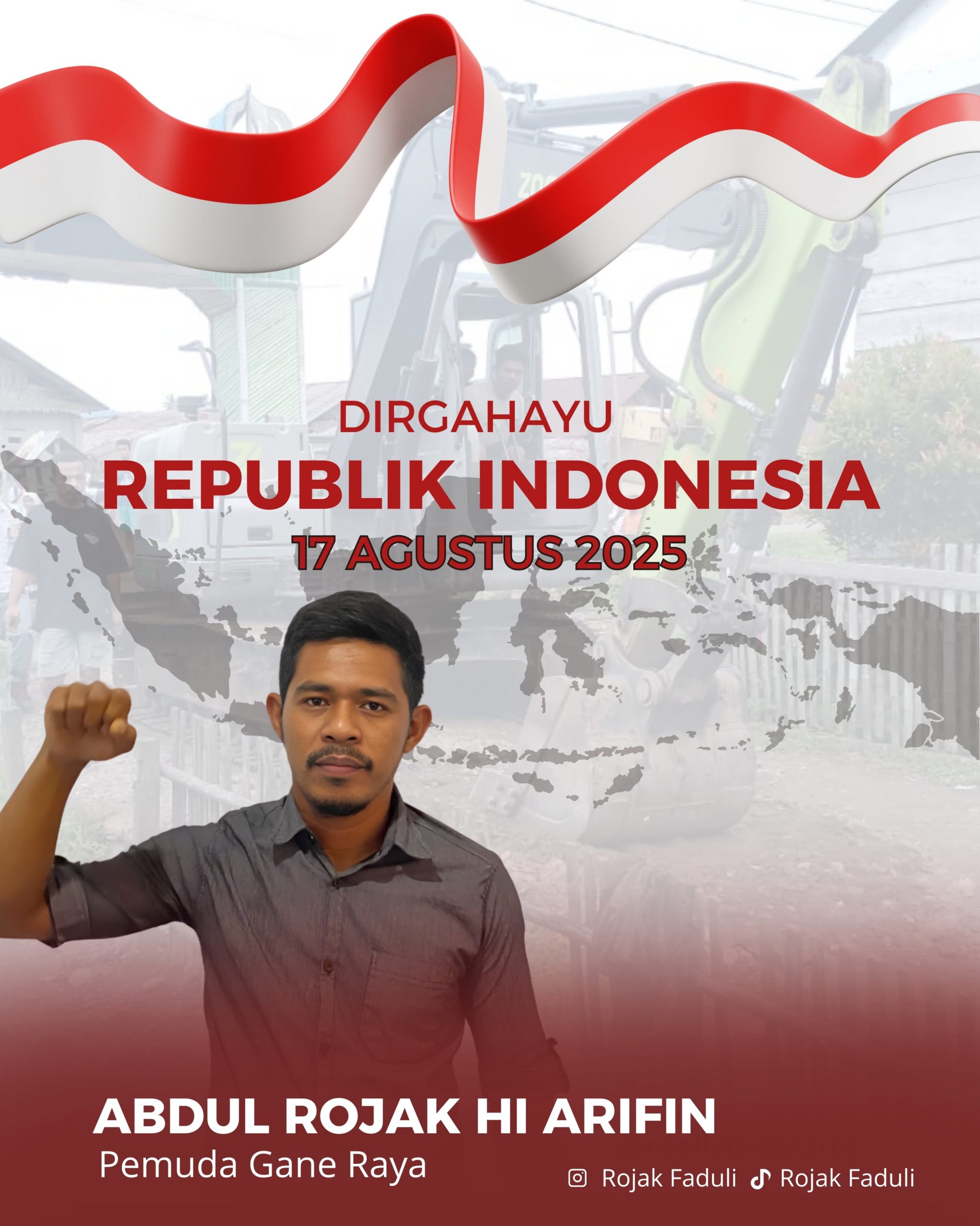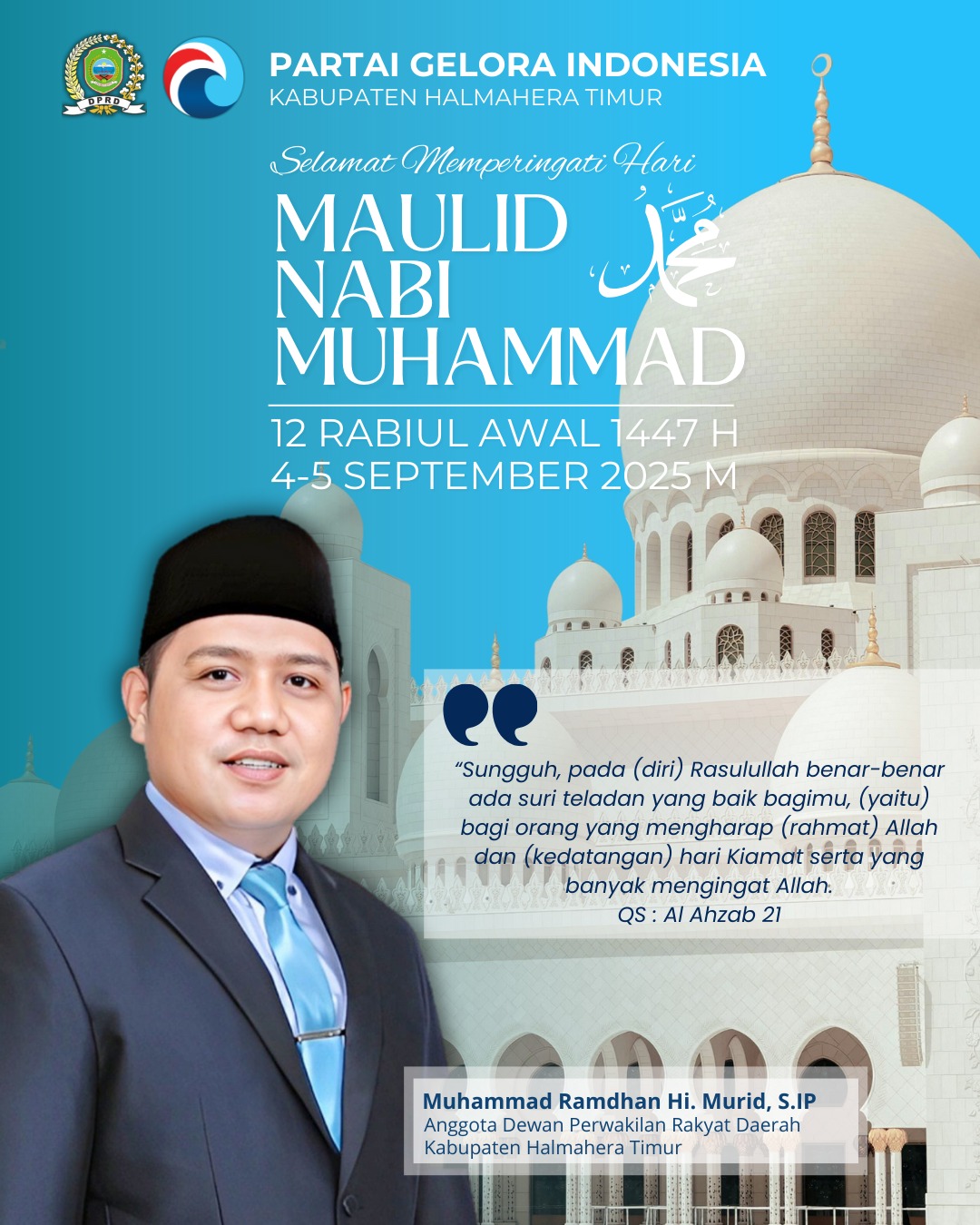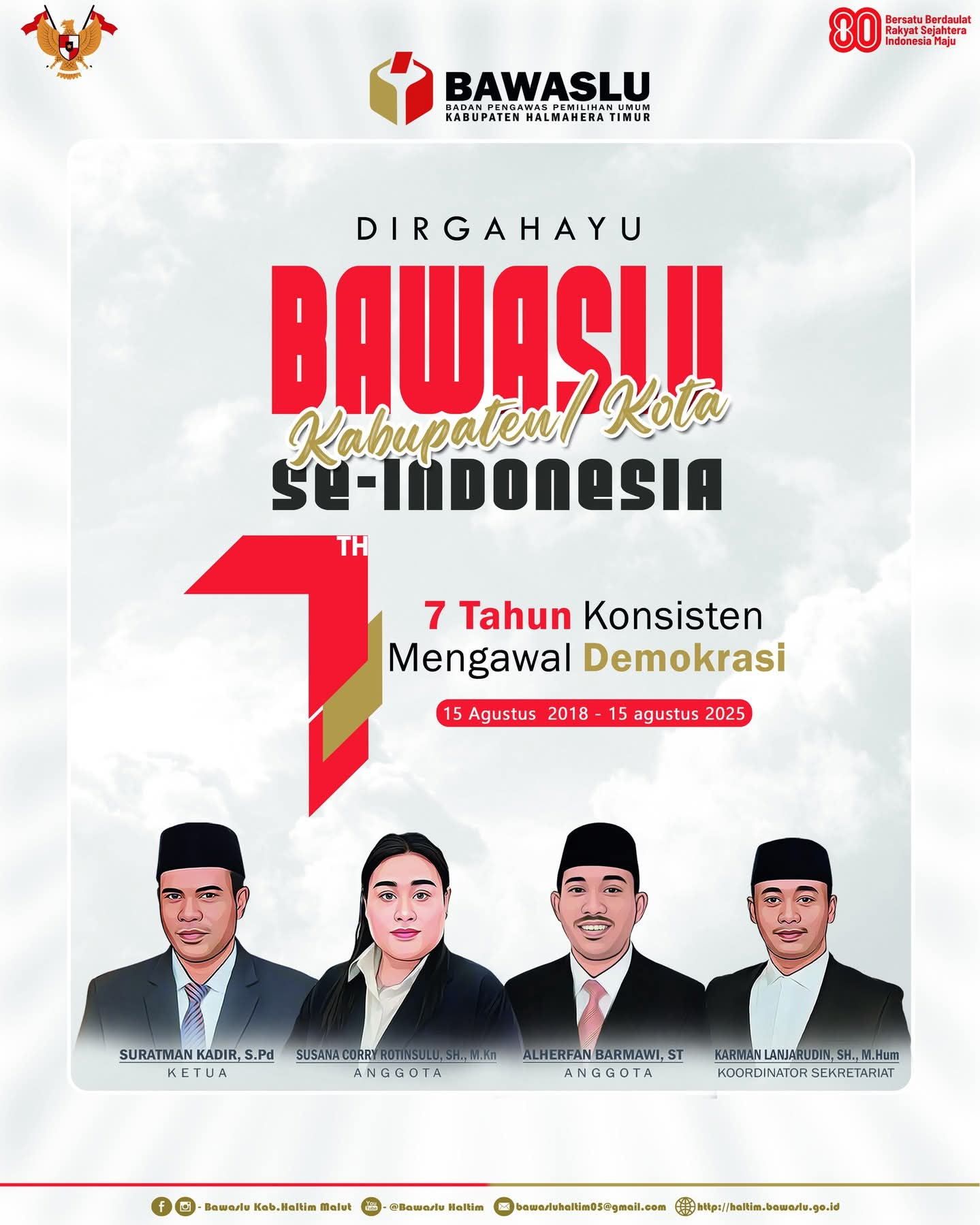Oleh : Sulfi NH Bugis
(Praktisi Pertanian dan Pemerhati Desa)
Mewakili para petani Di lembah Wasile-Timur Halmahera saya merasa gelisah. bagaimana tidak, ketika membaca peta pembangunan hari ini menampilkan kontras yang cukup tajam: satu sisi, aktivitas industri tambang yang gagah berdiri digadang-gadang sebagai mesin penggerak ekonomi baru, sementara itu di sisi yang lain, sektor pertanian yang semenjak lama menjadi sandaran hidup masyarakat pedesaan semakin terpinggirkan.
Dalam wacana publik, tambang dipromosikan sebagai simbol modernitas, lapangan kerja, dan sumber pendapatan daerah. Namun, di lapangan masalah dan pertanyaan besar muncul: bagaimana harga yang harus dibayar oleh petani, lahan pangan, dan ketahanan pangan lokal akibat ekspansi tambang?
Jika ditelusuri dari variabel lingkungan, masalahnya tampak jelas. Lahan sawah yang dulu menjadi kebanggaan daerah ini, kini dan bahkan kelak banyak berubah fungsi atau tidak lagi ditanami. Aktivitas tambang dengan pembukaan jalan, penggalian tanah, dan penimbunan material mengakibatkan lahan produktif berkurang secara signifikan. Air irigasi yang dahulu jernih kini sering membawa sedimen bahkan berpotensi terkontaminasi logam berat. Hal ini bukan sekadar isu teknis, melainkan ancaman nyata terhadap kualitas tanah dan air yang menjadi dasar produksi pangan. Penurunan pH tanah, menurunnya kadar bahan organik, hingga rusaknya ekosistem sagu sebagai pangan lokal adalah tanda-tanda degradasi yang sulit dibantah akhirnya.
Fakta ekologis tersebut tentu nya akan berimbas langsung pada variabel produktivitas pertanian. Data produksi padi sawah menunjukkan tren menurun, luas lahan tidur kian bertambah, dan hasil panen per hektar tidak sebanding dengan kebutuhan konsumsi lokal. Petani yang dulu menanam padi secara rutin kini menghadapi dilema: biaya produksi yang naik, risiko gagal panen akibat kualitas tanah menurun, serta keterbatasan akses terhadap alat mesin pertanian (alsintan). Bantuan benih unggul memang dibagikan, tetapi tanpa tanah subur dan air bersih, benih hanyalah simbol harapan yang rapuh.
Dampak lingkungan dan produktivitas ini kemudian merembet pada variabel sosial-ekonomi. Banyak petani akhirnya memilih meninggalkan sawah dan bekerja di sektor tambang. Secara jangka pendek, pilihan itu tampak rasional: gaji bulanan dari perusahaan tambang lebih cepat diterima dibanding menunggu hasil panen yang tidak pasti. Namun, secara jangka panjang, migrasi profesi ini mengikis basis petani produktif di Halmahera Timur. Pendapatan petani yang bertahan semakin tidak menentu, harga komoditas lokal tidak stabil, dan ketahanan pangan rumah tangga kian rapuh. Ironisnya, daerah yang pernah disebut lumbung pangan kini berpotensi menjadi konsumen setia beras impor dari luar Maluku Utara.
Mitigasi tentu sudah digembar-gemborkan. Beberapa program Pemerintah di level Desa secara bersama-sama telah mengupayakan program bantuan berupa bibit dan pupuk. Tetapi, pertanyaannya: seberapa efektif program-program tersebut? Berapa hektar lahan yang kini tidur benar-benar kembali produktif? Apakah bantuan benih unggul disertai pendampingan teknis dan perbaikan ekosistem tanah? Tanpa evaluasi yang transparan, program mitigasi cenderung berhenti pada angka seremonial yang enak didengar, tapi kosong di lapangan.
Dalam konteks kelembagaan, peran kelompok tani atau gapoktan juga belum maksimal. Mereka seringkali hanya menjadi penerima bantuan, bukan aktor utama dalam perumusan kebijakan mitigasi. Padahal, kearifan lokal dan pengalaman petani bisa menjadi bahan penting untuk menyusun strategi adaptasi. Jika kebijakan hanya top-down, maka suara petani akan semakin tenggelam di balik retorika pembangunan tambang.
Lebih jauh bahkan, soalan ini bukan sekadar soal sawah atau komoditas. Ia menyentuh jantung ketahanan pangan. Variabel ketahanan dan keberlanjutan pangan menegaskan bahwa cadangan pangan lokal di Halmahera Timur semakin terbatas. Indeks ketahanan pangan daerah rawan melemah jika produksi terus menurun sementara konsumsi meningkat. Apalagi, sagu sebagai pangan tradisional Maluku Utara juga terancam akibat ekspansi tambang yang menggerus hutan rawa. Ketika pangan lokal hilang, masyarakat tidak hanya kehilangan sumber energi, tetapi juga kehilangan identitas budaya.
Pertanyaannya: apakah keuntungan dari sektor tambang sepadan dengan kerugian pangan yang akan ditanggung masyarakat petani lokal wasile? Secara ekonomi, kontribusi tambang mungkin signifikan terhadap PAD, tetapi secara sosial dan ekologis, biaya yang ditanggung petani jauh lebih besar. Produktivitas pertanian menurun, pendapatan petani anjlok, ekosistem pangan lokal hancur, dan ketahanan pangan tergadai. Halmahera Timur bisa jadi kaya di atas kertas, tetapi miskin di dapur.
Oleh karena itu, kritik realistis ini perlu kita ajukan sebagai warning sekaligus reminder buat kita semua. Pertama, pemerintah daerah harus berani menempatkan lahan pangan berkelanjutan sebagai kawasan lindung yang tidak bisa dikompromikan dengan ekspansi tambang. Kedua, mitigasi tidak boleh hanya berhenti pada urusan simbolis, melainkan harus berbasis pada pemulihan ekologi nyata: perbaikan kualitas tanah, irigasi, dan akses teknologi pertanian. Ketiga, kebijakan pangan harus menekankan kemandirian dan diversifikasi, misalnya dengan menghidupkan kembali sagu, umbi-umbian, dan komoditi perkebunan lainnya sebagai komoditas strategis. Keempat, menempatkan posisi petani sebagai partisipan aktif untuk mengelola informasi dalam rangka penetapan kebijakan dan memperkuatnya secara proporsional.
Tambang memang bisa menjadi sumber devisa, tetapi pangan adalah sumber kehidupan. Jika Halmahera Timur terus membiarkan sektor pertaniannya terpinggirkan, maka keuntungan tambang hanyalah utang yang harus dibayar generasi berikutnya dengan harga mahal: hilangnya kedaulatan pangan dan rusaknya ruang hidup. Pada akhirnya, pilihan itu kembali pada arah kebijakan: maukah kita menukar sebutir beras dengan sebutir nikel?
___Mari Berdaya___