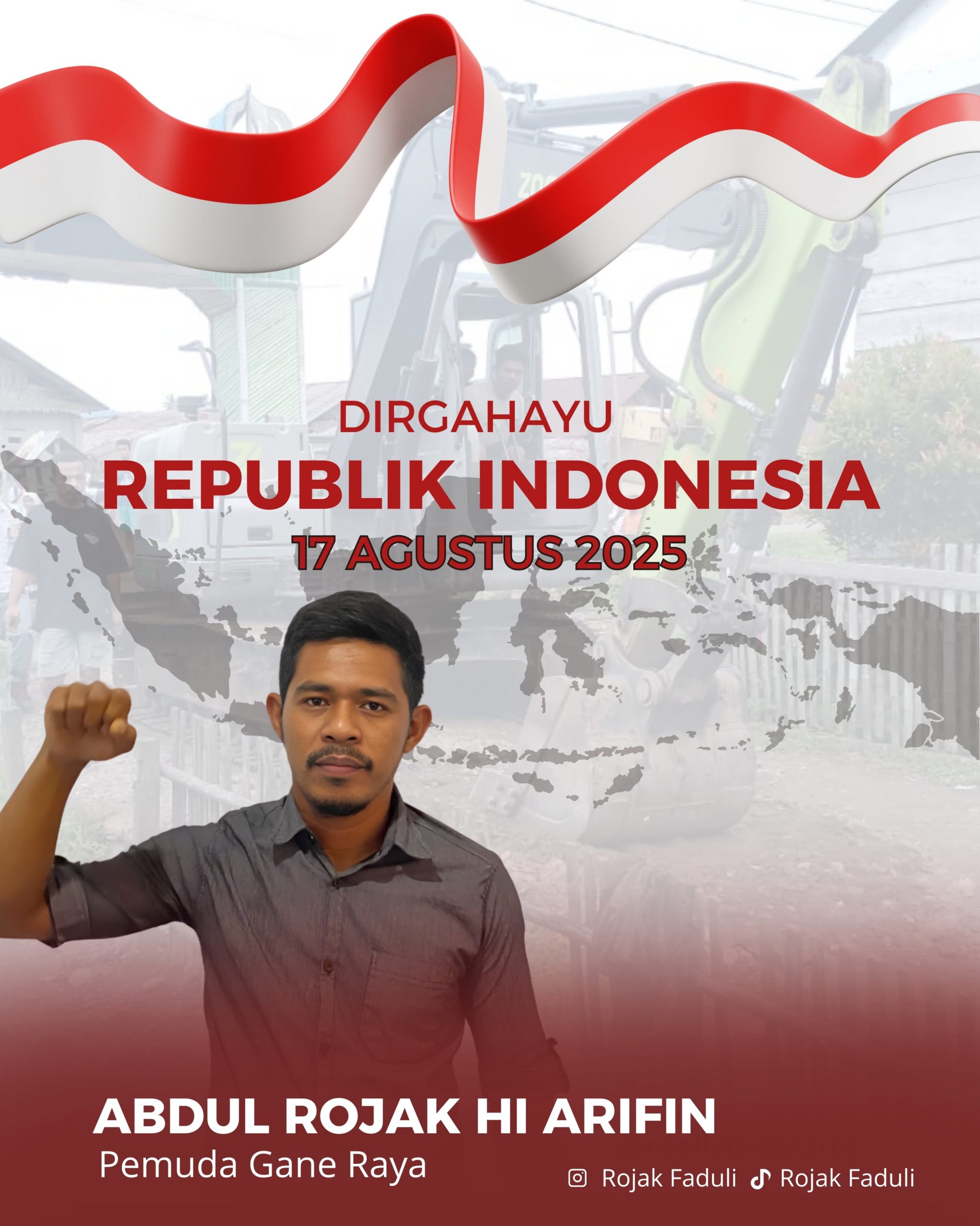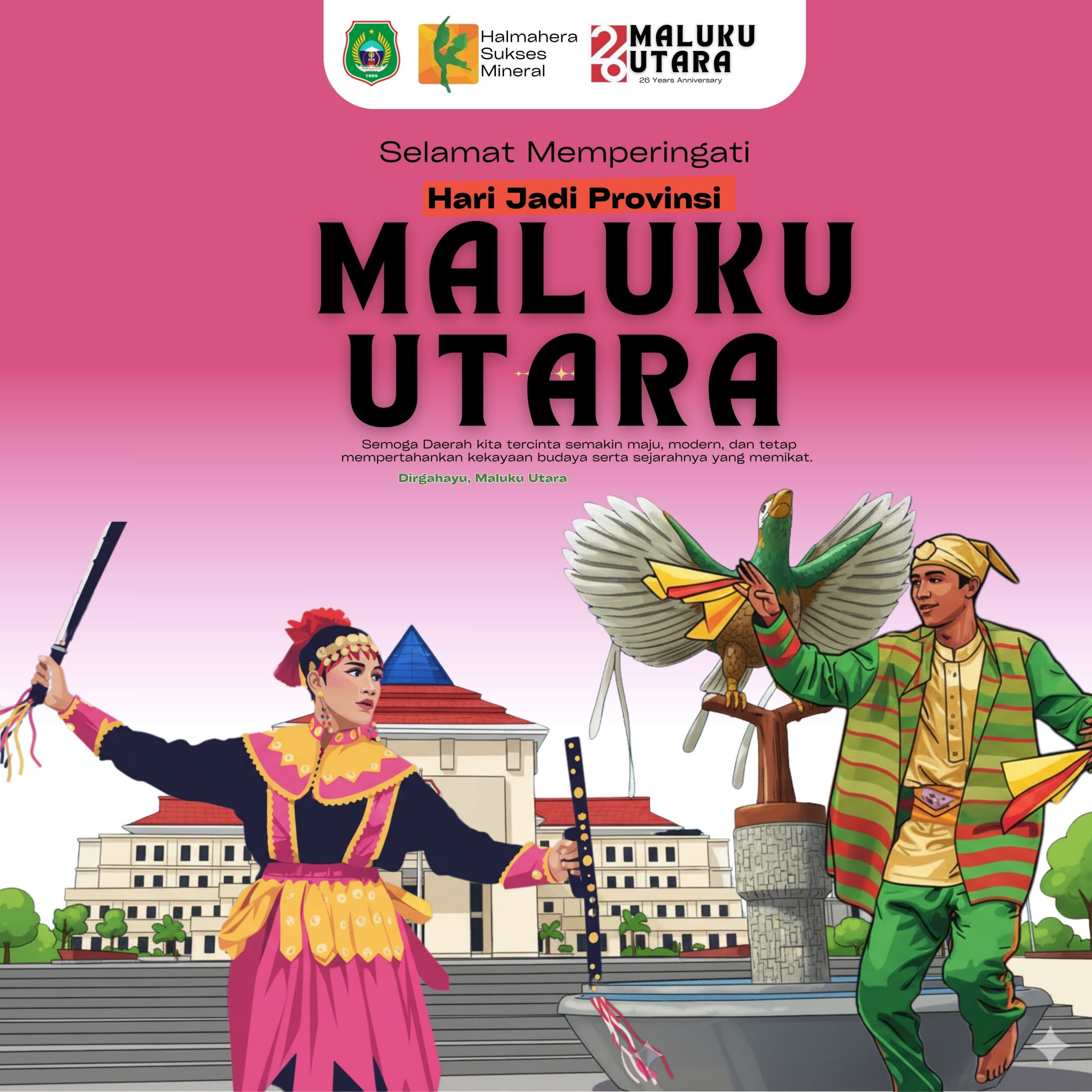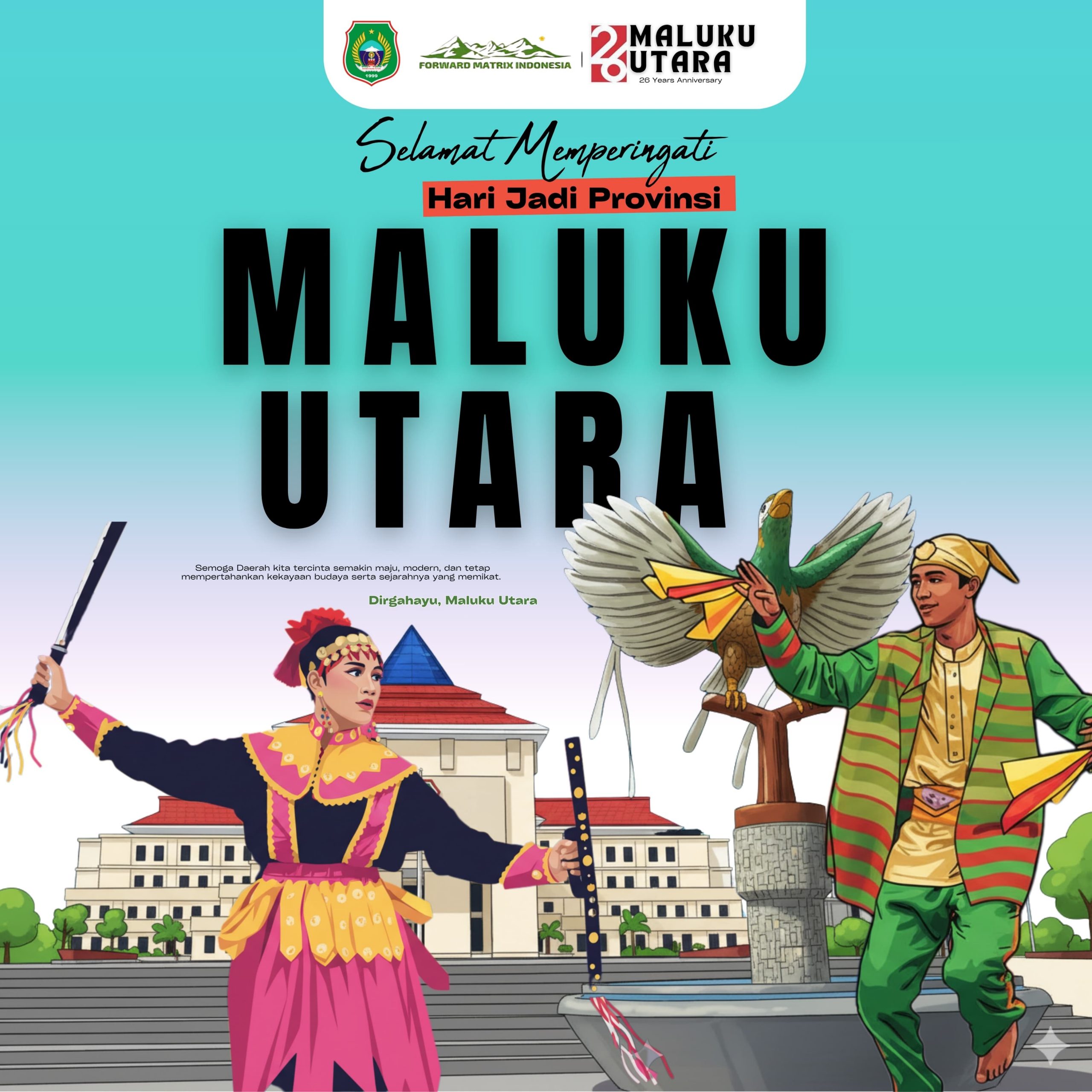Oleh: Fajrun Mustakim
Mahasiswa Universitas Airlangga
Maluku Utara, provinsi kepulauan yang dulu dikenal lewat hasil laut dan rempah, kini berubah menjadi panggung utama bagi hilirisasi nikel nasional. Dalam waktu singkat, tanah yang dahulu hijau dan tenang di Halmahera Tengah menjelma menjadi sabuk industri berat ketika deretan smelter, pelabuhan ekspor, dan truk-truk pengangkut bijih nikel yang tak henti melintas. Di atas kertas, provinsi ini adalah salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alam paling melimpah di Indonesia. Dari nikel di Halmahera Tengah dan Timur, emas di Halmahera Selatan, hingga biji besi di Kepulauan Sula, Maluku Utara seolah dikaruniai potensi ekonomi luar biasa. Namun, di balik itu semua, tersimpan realitas pahit bahwa tingkat kemiskinan yang tetap tinggi, ketimpangan yang melebar, dan masyarakat lokal yang makin terpinggirkan dari sumber penghidupan.
Bagi banyak pihak, ini adalah simbol kemajuan tanda bahwa Indonesia timur akhirnya “berdiri sejajar” dalam arus industrialisasi global. Namun di balik gemuruh mesin dan deru ekspor, pertanyaannya muncul: apakah Maluku Utara benar-benar sedang tumbuh, atau justru sedang digerakkan oleh mesin pertumbuhan yang rapuh dan timpang?
Badan Pusat Statistik mencatat, ekonomi Maluku Utara tumbuh luar biasa 13,73% pada Tahun 2024 dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan (tinggi) pada Triwulan II Tahun 2025 dengan pertumbuhan 32,09% (year-on-year). Laju yang menyalip seluruh provinsi dan menjadi yang tertiggi di Indonesia hingga saat ini, bahkan sektor pertambangan dan penggalian mencatat lonjakan sebesar 60,57% (yoy). Angka-angka ini tampak seperti kisah sukses pembangunan modern: ekspor naik, investasi asing masuk, dan daerah yang dulu tertinggal kini menjadi kontributor besar terhadap produk domestik nasional.
Namun di balik angka itu, muncul paradoks. Pertumbuhan Maluku Utara kini berdiri di atas pijakan yang sempit antara satu komoditas, satu sektor, dan satu model ekonomi (ekstraksi sumber daya alam).
Dalam ekonomi pembangunan, ini disebut sebagai “growth without diversification”, di mana kemakmuran bergantung pada sumber daya alam yang mudah menguap nilainya. Hari ini nikel mungkin menguntungkan, tetapi seperti minyak di tahun 1970-an, harga global bisa jatuh sewaktu-waktu, dan dengan itu, kesejahteraan yang dibangun di atasnya ikut runtuh.
Ekonomi yang Bertumpu pada Tanah yang Terkikis dan Gurita Bisnis Gubernur
Berdasarkan Laporan JATAM (2024) menunjukkan Maluku Utara kini memiliki 127 izin tambang, mencakup lebih dari 650 ribu hektar lahan, atau hampir seperempat luas daratan provinsi. Khusus di Halmahera Tengah, sekitar 42% wilayah daratan telah menjadi konsesi pertambangan.
Angka-angka ini tidak sekadar statistik, melainkan gambaran konkret tentang bagaimana ruang hidup berubah menjadi ruang produksi. Hutan yang dulu menjadi penyangga kehidupan kini menjadi sumber material, sungai menjadi jalur limbah, dan udara dipenuhi debu dari aktivitas smelter.
Kawasan industri seperti IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park) memang menciptakan ribuan lapangan kerja, tetapi sebagian besar bersifat kontrak, bergaji rendah, dan belum seluruhnya dinikmati oleh masyarakat lokal.
Sebagian besar posisi teknis dan manajerial masih diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah bahkan luar negeri. Ironisnya, masyarakat yang lahannya diambil untuk tambang seringkali tidak ikut menikmati hasilnya mereka hanya melihat kilau pabrik di kejauhan, sementara hutan dan laut tempat mereka mencari nafkah perlahan menghilang.
Dibalik narasi “Pembangunan Berkelanjutan” publik menemukan cerita lain yaitu; gurita bisnis Gubernur Maluku Utara. Berdasarkan Penelusuran JATAM menunjukkan bahwa Gubernur Maluku Utara, melalui PT Jaringan Bela Group, memiliki kepemilikan saham dan hubungan bisnis dengan sedikitnya enam perusahaan ekstraktif besar: PT Indonesia Mas Mulia, PT Amazing Tabara, PT Bela Sarana Permai, PT Karya Wijaya, PT Bela Kencana, dan PT Bela Karya Jaya, namun 2 perusahaan telah di cabut izinnya pada tahun 2022 yaitu PT Amazing Tabar dan PT Bela Kencana.
Berdasarkan pada Laporan tersebut, Gubernur Maluku Utara (Sherly Tjoanda) memiliki sekitar 750 lembar saham di PT Karya Wijaya dan menjabat sebagai komisaris utama dan Bapak Benny Laos (Alm) memiliki sekitar 1.625 lembar Saham. Bahkan dalam berbagai pemberitaan menyebutkan bahwa Gubernur Maluku Utara tersebut memiliki sekiranya 71% saham pada PT Karya Wijaya dengan produksi Nikel dan memiliki luas Deforestasi (kehilangan/Kerusakan Hutan) sekitar 152 Ha.
Belum lagi PT Indonesia Mas Mulia yang mengantongi IUP Emas seluas 4.800 hektar dengan nomor perizinan 502/5/DPMPTSP/X2018 yang berlokasi di Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, Halmahera Selatan dengan kepemilikan saham mayoritas dari PT Balaco yang menguasai sekiranya 21.250 lembar saham. Di PT balaco Bapak Benny Laos (Alm) memiliki sekiranya 3.000 lembar saham yang mengikuti PT Bela Group yang menguasai sekitar 7.000 lembar saham. PT Bela Group adalah Perusahan Holding (pemegang) dengan kepemilikan saham dari Gubernur Maluku Utara (Sherly Tjoanda) sebagai direktur yang menguasai 25.500 lebar saham dan Bapak Benny (Alm) Laos sekitar 75.500 lembar saham.
Dari keenamnya Perusahan tersebut bergerak di bidang tambang nikel, emas, dan pasir besi. Dengan portofolio seperti itu, wajar jika arah kebijakan provinsi Maluku Utara berpihak penuh kepada sektor tambang. Jadi secara sederhana kita memahami bahwa gubernur adalah bagian dari ekosistem bisnis tambang itu sendiri, bahkan Bappeda Maluku Utara memasukkan “hilirisasi nikel” sebagai prioritas RPJPD 2025–2045, tetapi tidak menyebut satu pun strategi untuk mengatasi krisis lingkungan.
Pertumbuhan yang Tak Merata dan Tak Menyentuh Akar
Maluku Utara memang mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, tetapi juga menanggung paradoks Ekstraktivisme: daerah kaya sumber daya, tapi rakyatnya miskin. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan tingkat kemiskinan berada di angka 5,81% pada maret 2025 sedikit menurun dari 6,03% (2024). Namun di wilayah tambang, angka kemiskinan justru jauh lebih tinggi, Halmahera Timur 11,91% pada tahun 2024, Halmahera Tengah 10,71%, Halmahera Selatan 5,63%. Dan Kota Ternate, yang tidak bergantung pada tambang, justru paling rendah angka kemiskinannya (3,14%) pada tahun (2024). Artinya, kemiskinan di Maluku Utara bukan karena kurangnya tambang, tapi karena tambang terlalu banyak tanpa kontrol dan pemerataan. Bahkan penduduk miskin di Maluku Utara yang tinggal di pedesaan mereka kehilangan akses terhadap tanah dan laut akibat proyek industri nikel. Pendapatan naik di sekitar kawasan industri, tapi biaya hidup melonjak lebih cepat, bahkan harga bahan pokok, air bersih, dan sewa rumah meningkat tajam.
Pertumbuhan yang tinggi di tingkat makro tak pernah menyentuh meja makan rakyat kecil. Inilah bentuk kemiskinan struktural di mana sistem ekonomi dan politik dirancang untuk menguntungkan elite, bukan masyarakat.
Kritik utama terhadap model pembangunan seperti ini adalah ketimpangan spasial dan ketimpangan sektoral yang semakin melebar. Di satu sisi, Halmahera Tengah dan kawasan industri Weda tumbuh pesat; di sisi lain, kabupaten seperti Morotai, Taliabu, atau Kepulauan Sula masih bergulat dengan masalah dasar: kemiskinan, infrastruktur, dan pengangguran.
Daya beli memang naik di sekitar tambang, tetapi di luar itu, harga kebutuhan melonjak, biaya hidup meningkat, dan sebagian besar masyarakat tetap bekerja di sektor informal.
Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi ternyata tidak otomatis berarti kesejahteraan yang meluas. Lebih jauh lagi, struktur ekonomi Maluku Utara menjadi rapuh. Ketika sektor pertambangan dan industri pengolahan mendominasi, sektor lain seperti pertanian dan perikanan yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi lokal akan semakin tersisih.
Lahan produktif berkurang, nelayan kehilangan akses ke laut karena kawasan industri, dan generasi muda lebih memilih bekerja di pabrik daripada bertani. Dalam jangka panjang, ini menciptakan ketergantungan ekonomi tunggal dan mengikis fondasi kemandirian daerah.
Tak bisa dipungkiri bahwa fenomena yang kini melanda Maluku Utara memiliki kemiripan dengan gejala Dutch Disease yang pernah dialami banyak negara penghasil sumber daya alam. Ketika satu sektor menghasilkan surplus besar, sumber daya baik tenaga kerja, modal, maupun kebijakan publik tersedot ke sana, sementara sektor lain merana.
Dalam situasi seperti ini, pertumbuhan ekonomi tinggi justru dapat menjadi ilusi kesejahteraan karena pertumbuhan yang tak menyentuh masyarakat, dan tak menyiapkan masa depan ketika nikel habis.
Kita sedang menyaksikan paradoks kemajuan, di mana indikator makro membaik sementara kualitas hidup masyarakat sekitar tambang stagnan, bahkan memburuk akibat degradasi lingkungan.
Dampak Lingkungan
Tidak ada pertumbuhan tanpa jejak ekologis. Di Teluk Weda, tempat berdirinya kompleks IWIP, masyarakat melaporkan pencemaran air laut, penurunan hasil tangkapan ikan, dan kerusakan terumbu karang. Bahkan berdasarkan laporan dari Climate Rights International (2024) mencatat adanya penggusuran komunitas lokal, hilangnya sumber air bersih, dan meningkatnya konflik sosial antara warga dan perusahaan.
Dalam istilah ekonomi lingkungan, ini disebut eksternalitas negatif dimana biaya sosial yang tidak masuk ke dalam perhitungan PDRB. Sementara pemerintah dan investor berbicara tentang “green transition” dan “baterai untuk energi bersih dunia,” realitas di lapangan justru menunjukkan paradoks hijau di mana nikel yang menyalakan mobil listrik global lahir dari tanah yang kehilangan vegetasi dan masyarakat yang kehilangan ruang hidup.
Maluku Utara hari ini berdiri di persimpangan jalan. Jika terus bertumpu pada pertambangan, provinsi ini berisiko mengulangi skenario klasik resource curse dimana kaya sumber daya, tetapi miskin diversifikasi dan rentan krisis.
Pemerintah daerah tampak terpesona oleh angka pertumbuhan Ekonomi yang tinggi, seolah itu menandakan kemajuan sejati, padahal pertumbuhan semacam ini mudah runtuh ketika harga nikel global jatuh atau izin tambang habis masa berlakunya.
Kebijakan pembangunan harus berani melampaui euforia hilirisasi. Hilirisasi bukan sekadar membangun smelter, melainkan memastikan transfer pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan kepada masyarakat lokal. Tanpa itu, hilirisasi hanya menjadi bentuk baru dari ekstraksi tambang ke pabrik, tapi tetap tanpa nilai tambah sosial.
Untuk membangun ekonomi Maluku Utara yang tangguh dan berkeadilan, diperlukan perubahan paradigma dimana pertambangan harus menjadi batu loncatan, bukan penopang abadi. Pendapatan dari sektor ini perlu diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi alternatif pertanian modern, perikanan olahan, pariwisata bahari, dan UMKM digital.
Ekonomi yang kuat bukanlah ekonomi yang bergantung pada bumi yang terus digali, melainkan ekonomi yang mampu berdiri tegak bahkan ketika tambang terakhir telah ditutup. Disitulah tantangan terbesar Maluku Utara untuk menemukan keseimbangan antara emas di perut bumi dan masa depan di tangan manusia. Dan yang terakhir, kebijakan lingkungan harus menempatkan manusia dan ekosistem sebagai pusat pembangunan, bukan sekadar pelengkap laporan AMDAL.