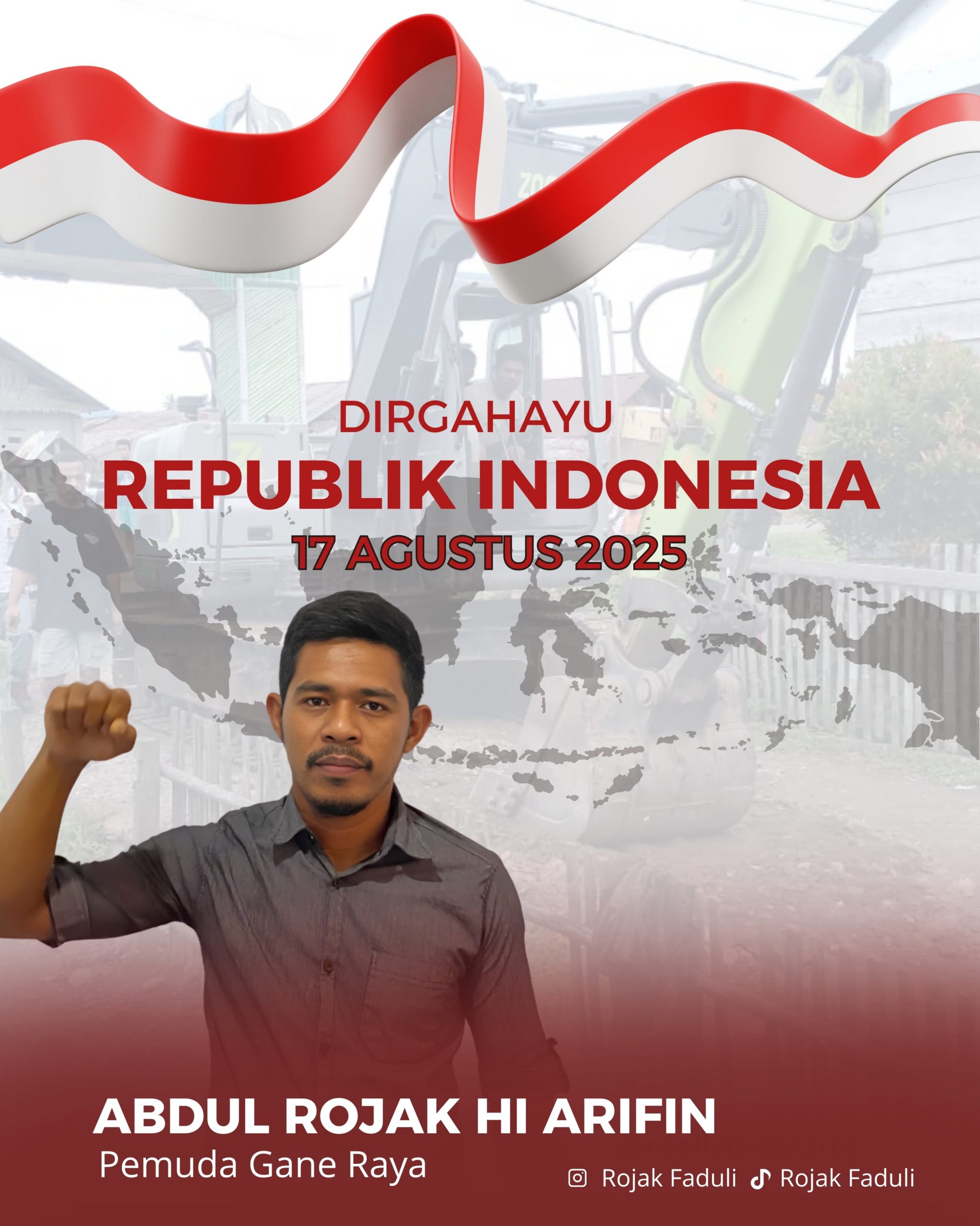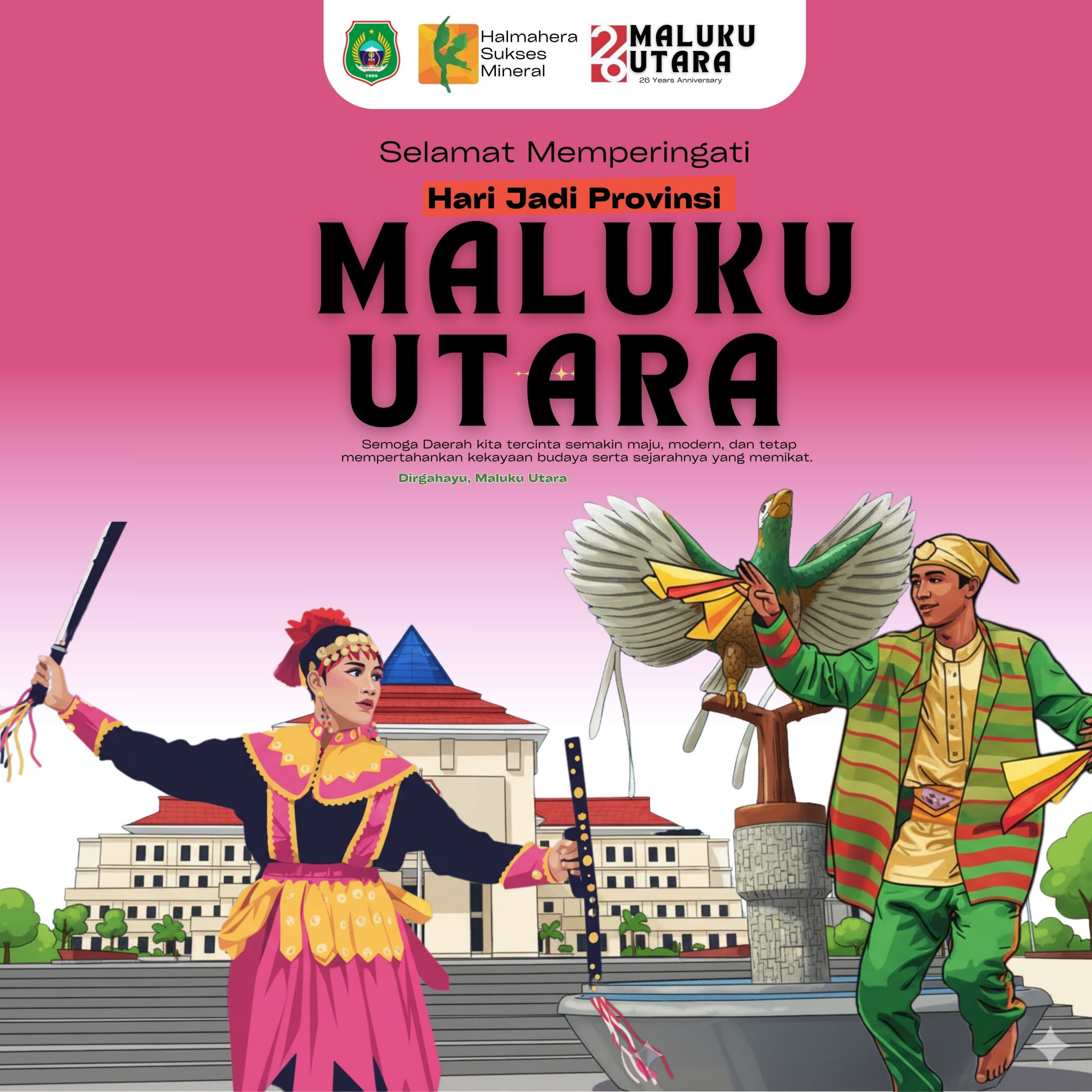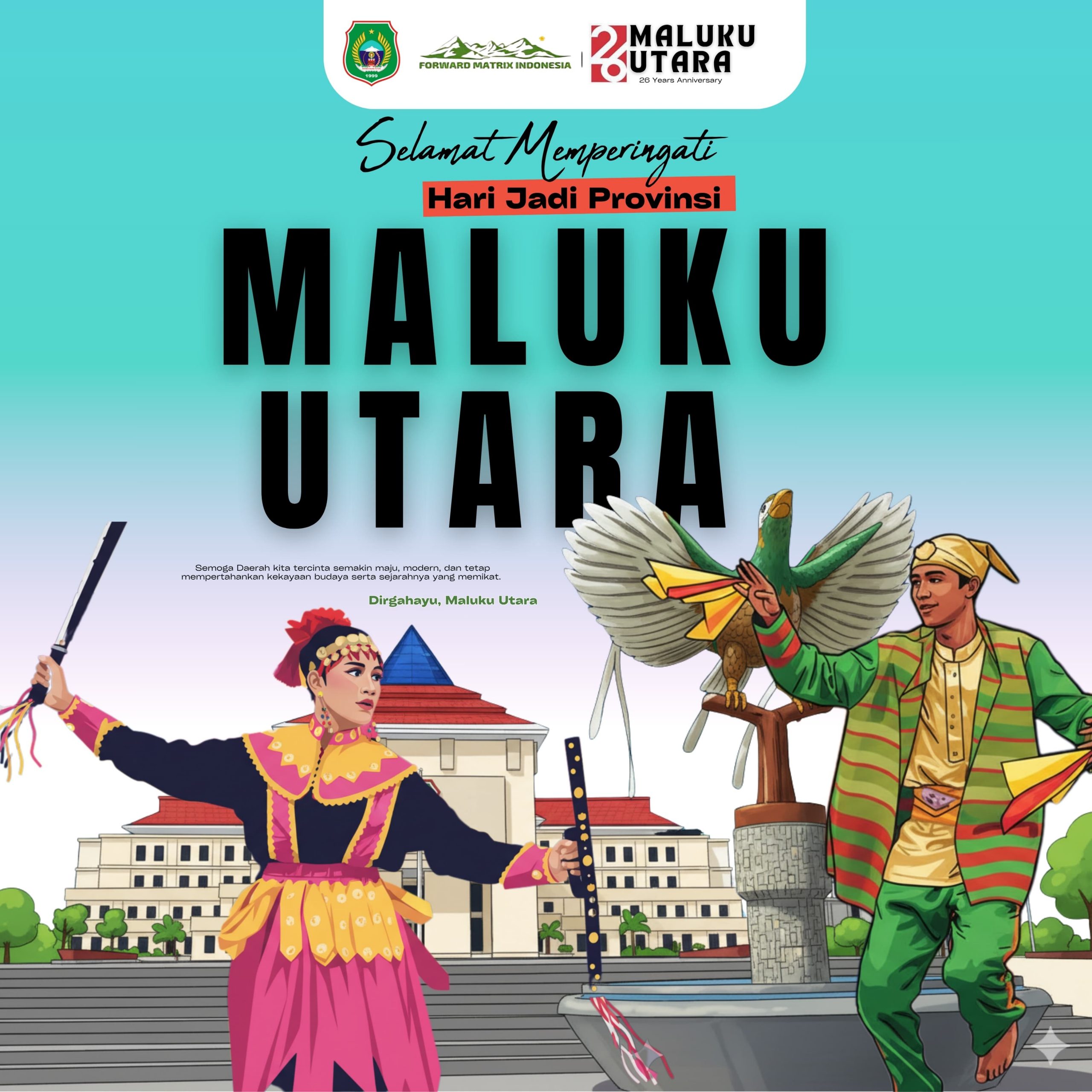Oleh: Aisyah A. Mailaha
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Khairun Ternate
Provinsi Maluku Utara memiliki posisi geografis yang sangat strategis: wilayah kepulauan yang berada di jalur perdagangan nasional dan internasional, kaya akan sumber daya alam, dan diberkahi keindahan alam bahari yang luar biasa. Namun, potensi besar ini masih dibayangi oleh tantangan struktural yang serius—ketimpangan pembangunan, konflik batas wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar, dan kerentanan terhadap bencana.
Sebagai wilayah yang terbentuk dari ratusan pulau, Maluku Utara membutuhkan pendekatan perencanaan wilayah yang lebih dari sekadar membangun jalan atau pelabuhan. Yang dibutuhkan adalah visi pembangunan yang menyeluruh—berbasis data spasial, berwawasan lingkungan, dan menjunjung tinggi keadilan antarwilayah. Sayangnya, hingga hari ini, kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota masih nyata terlihat. Kota-kota seperti Ternate dan Tidore berkembang pesat, sementara wilayah seperti Halmahera Timur dan Kepulauan Sula terus tertinggal dalam hal akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur konektivitas.
Konflik batas wilayah pun menjadi ironi tersendiri di tengah semangat otonomi daerah. Perselisihan seperti yang terjadi di enam desa di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur bukan hanya menghambat pelayanan publik, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang bisa memecah rasa kebersamaan sebagai satu provinsi. Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah memegang peran krusial sebagai mediator dan pemimpin visi pembangunan yang inklusif.
Baca Juga:
Menatap Masa Depan Perikanan Indonesia dengan Pengelolaan Berkelanjutan
Membangun Maluku Utara Melalui Perencanaan Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Selain tantangan administratif, perencanaan wilayah di Maluku Utara juga dihadapkan pada risiko bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir, tempat sebagian besar penduduk bermukim, sangat rentan terhadap bencana, dan penanganannya tidak cukup hanya dengan rencana kontingensi musiman. Harus ada integrasi antara sistem informasi geografis (SIG), peringatan dini, dan tata ruang yang melarang pembangunan di zona merah bencana. Penelitian seperti yang dilakukan di Sanana, Kepulauan Sula, membuktikan bahwa pendekatan berbasis data spasial dapat menyelamatkan banyak nyawa di masa depan.
Namun bukan berarti Maluku Utara kekurangan arah. Dokumen resmi seperti RTRW 2013–2033 dan RPIW 2023–2029 telah menyusun strategi pengembangan kawasan strategis seperti Ternate–Tidore–Sofifi serta pembangunan konektivitas maritim dan udara. Ini merupakan langkah positif. Namun, rencana yang baik tanpa pelaksanaan yang adil dan partisipatif hanya akan menjadi tumpukan dokumen di rak-rak kantor pemerintahan.
Di sinilah urgensinya memperkuat partisipasi masyarakat, melalui forum seperti Musrenbang, untuk memastikan bahwa suara desa terpencil mendapat tempat yang sama pentingnya dengan suara pusat provinsi. Rakyat bukan hanya objek pembangunan, tapi subjek yang harus didengar dan dilibatkan.
Kesimpulan saya sederhana: masa depan Maluku Utara sangat menjanjikan, tapi jalan menuju ke sana penuh rintangan. Butuh komitmen bersama—antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta—untuk menciptakan tata ruang yang adil, tangguh, dan berkelanjutan. Jika tidak, potensi besar yang dimiliki provinsi ini akan terus menjadi cerita yang belum selesai ditulis.